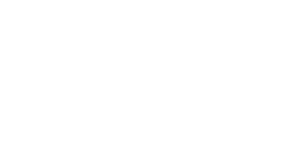Oleh: Nashrul Mu’minin
LPCR.OR.ID – Isu lama kembali dihidupkan di media sosial: warga Muhammadiyah dituding tidak gemar bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Narasi ini sontak menuai pro-kontra, seakan menjadi bahan bakar baru dalam polarisasi umat. Padahal, jika ditilik jujur, shalawat merupakan ajaran yang diterima semua ormas Islam, hanya berbeda pada bentuk dan cara ekspresinya. Muhammadiyah melalui Ajengan Wawan Gunawan (September 2025) dengan tegas menepis tuduhan itu, menegaskan bahwa umat Muhammadiyah tetap bershalawat, baik dalam shalat maupun di luar shalat—hanya saja lebih sederhana, tidak selalu berjamaah panjang.
Tuduhan tersebut, menurut saya, lahir dari bias lama terhadap Muhammadiyah. Seolah ada standar tunggal untuk mengukur kecintaan umat kepada Nabi: semakin keras dan meriah melantunkan shalawat, semakin sahih pula keimanan. Padahal, Islam tidak pernah menetapkan ukuran semacam itu. Tulisan ini bertujuan menjernihkan kabut isu, membongkar bias yang sering dipelihara, dan menunjukkan bahwa perbedaan ekspresi ibadah tidak seharusnya menjadi alasan untuk menegasikan kelompok lain.
Data justru memperlihatkan keragaman ekspresi itu nyata di tengah umat. Survei LSI (2023) mencatat 83% muslim Indonesia rutin membaca shalawat. Namun bentuknya bervariasi: 41% memilih berjamaah dengan rebana, 39% lebih individual dan singkat, sementara 21% hanya di momen tertentu.^1 Artinya, perbedaan praktik shalawat bukan monopoli satu ormas, melainkan bagian dari mozaik besar keberagamaan muslim Indonesia.
Sejak berdirinya pada 1912, Muhammadiyah memang punya ciri pembaruan: ibadah dikembalikan pada substansi. Dalam Qaidah-Qaidah Majelis Tarjih (2010), jelas disebutkan shalawat adalah doa yang diperintahkan Allah (QS. Al-Ahzab: 56). Bedanya, Muhammadiyah menekankan agar shalawat tidak sekadar jadi ritual seremonial, melainkan sarana meneladani akhlak Nabi. Jadi, menolak? Tidak. Hanya memilih bentuk yang lebih esensial.
Sayangnya, framing media sosial sering menggiring opini sebaliknya. Beberapa akun sengaja mengangkat potongan kecil lalu menjadikannya generalisasi bahwa Muhammadiyah “kering shalawat”. Ini praktik cherry picking yang tidak adil. Nyatanya, di masjid-masjid Muhammadiyah, bacaan shalawat tetap hadir dalam shalat, khutbah, hingga acara keislaman. Yang berbeda hanya suasana dan formatnya.
Menurut saya, problem sebenarnya bukan pada ada atau tidaknya shalawat, melainkan pada rendahnya penghargaan terhadap keragaman. Indonesia adalah rumah besar dengan tradisi pesantren, tarekat, Muhammadiyah, dan banyak lagi. Setiap ormas punya cara sendiri mengungkapkan kecintaan pada Nabi. Tuduhan semacam ini lebih terasa bernuansa identitas—bahkan politis—daripada analisis keagamaan yang sehat.
Data Kementerian Agama (2024) juga mempertegas: 89% umat Islam rutin membaca shalawat dalam shalat lima waktu, sisanya di momen tertentu. Jika dipetakan ke afiliasi ormas, Muhammadiyah tetap masuk kelompok tinggi, meski ekspresinya cenderung individual dibanding NU yang mengutamakan tradisi berjamaah.^2 Fakta ini cukup membongkar tuduhan yang sempat viral.
Kesimpulannya, tudingan Muhammadiyah tidak bershalawat adalah salah kaprah. Shalawat memang hidup di seluruh ormas Islam, hanya saja bentuknya berbeda. Muhammadiyah menekankan substansi, NU menekankan kebersamaan, kelompok lain mungkin memberi aksen budaya. Semua sahih. Justru tantangan kita bukan pada siapa lebih banyak bershalawat, melainkan pada kemampuan menjaga ukhuwah dalam cinta yang sama kepada Nabi Muhammad SAW.